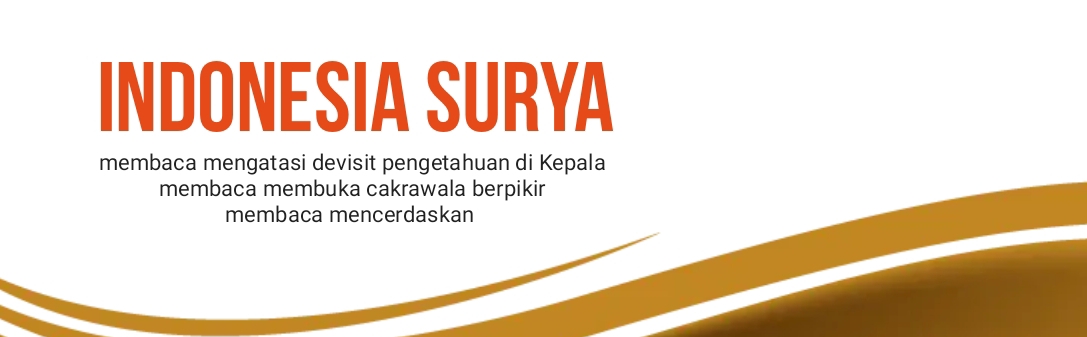Tulisan Erich menampilkan gaya retoris yang tajam. Erich secara cerdas memanfaatkan analogi film Office Space sebagai pintu masuk untuk mengkritik birokrasi pemerintah daerah. Satir yang digunakan menghibur, tetapi juga menyentil kesadaran pembaca akan absurditas rutinitas administratif yang kering makna.
Kutipan dari Charlie Chaplin dan Hannah Arendt memperkaya dimensi filosofis tulisan ini, memperluas cakrawala pembaca untuk melihat persoalan birokrasi dari sudut pandang eksistensial dan historis.
Kritik terhadap kebijakan juga disampaikan secara kontekstual.
Penulis menyoroti lomba Titi Jagung dan Mengetik Cepat sebagai contoh konkret dari kebijakan yang dinilai seremonial dan minim dampak. Keberanian penulis dalam mempertanyakan logika kebijakan tersebut menunjukkan sikap kritis yang dibutuhkan dalam ruang publik demokratis, sekaligus mengajak pembaca untuk tidak menerima kebijakan secara pasif.
Tulisan ini juga menunjukkan kedalaman analisis sosial dan ekonomi. Erich mengangkat ketimpangan antara pelaku ekonomi rakyat, khususnya ibu-ibu petani jagung titi, dan para ASN yang justru dijadikan aktor utama dalam perlombaan yang tidak relevan dengan realitas produksi.
Erich juga mengaitkan kritiknya dengan konsep manajemen rantai pasok (supply chain management) dan pentingnya keberpihakan kebijakan terhadap UMKM, sehingga kritik yang disampaikan tidak berhenti pada retorika, tetapi menyentuh akar persoalan struktural.
Teori filosofis dari Hannah Arendt tentang labor, work, dan action menjadi fondasi konseptual yang kuat dalam membedah stagnasi birokrasi. Erich tidak hanya mengutip, tetapi juga mengaplikasikan konsep tersebut secara kontekstual.
Analogi “tukang vs arsitek” menjadi ilustrasi yang tajam tentang peran ideal pemerintah: bukan sekadar pelaksana rutin, tetapi perancang masa depan yang visioner dan transformatif.
Tulisan ini memiliki kekuatan retoris yang tajam, namun secara struktural cenderung padat dan melebar. Paragraf-paragrafnya panjang dan kadang repetitif, sehingga pembaca bisa kehilangan fokus terhadap gagasan utama.
Untuk memperjelas alur dan memperkuat daya analisis, tulisan ini sebaiknya dibagi ke dalam sub bagian tematik yang lebih sistematis, seperti: kritik kebijakan Pemda, analisis sosial ekonomi jagung titi, kritik terhadap logika kerja birokrasi, serta solusi dan rekomendasi kebijakan. Pembagian ini akan membantu pembaca memahami arah kritik dan memperjelas posisi penulis terhadap isu yang diangkat.
Selain itu, terdapat beberapa pernyataan yang bersifat general dan perlu diperjelas agar tidak menimbulkan kesan hiperbolik atau ofensif. Misalnya, ungkapan “ASN dianggap tak berbeda dengan anak-anak SD” atau “Nasir-Tuaq Tipu” perlu dijelaskan konteks dan maksudnya secara lebih hati-hati. Tanpa penjelasan yang memadai, frasa-frasa tersebut bisa mengaburkan substansi kritik dan mengurangi kredibilitas argumen. Untuk memperkuat klaim, Erich disarankan menggunakan data atau kutipan resmi, seperti jumlah UMKM jagung titi yang aktif, anggaran yang dialokasikan untuk lomba, atau hasil survei kepuasan ASN terhadap program Pemda.
Tulisan ini juga sangat fokus pada kritik, namun belum cukup memberi ruang bagi kemungkinan niat baik di balik kebijakan perlombaan. Padahal, dalam konteks perayaan HUT Otonomi Daerah, perlombaan bisa saja dimaksudkan sebagai sarana edukasi, promosi budaya lokal, atau penguatan solidaritas antar-OPD. Karena itu, Erich perlu menambahkan paragraf yang mengakui potensi positif dari kegiatan tersebut, sembari tetap menekankan bahwa desain dan pelaksanaannya harus diarahkan pada dampak strategis dan berkelanjutan.
Beberapa klaim yang sangat kuat secara naratif, seperti “sistem pasar yang tidak ramah” atau “ibu-ibu tidur di selasar pasar,” akan lebih kokoh jika didukung oleh referensi empiris. Penambahan data dari laporan UMKM, berita lokal, atau hasil observasi lapangan akan memberikan bobot akademik dan memperkuat validitas kritik. Dengan dukungan data, tulisan ini tidak hanya menjadi refleksi kritis, tetapi juga bisa menjadi masukan kebijakan yang konstruktif dan berdampak.
Kedua: Respons terhadap tulisan Erich Wajah Simbolik Jabatan: Bahasa,Kuasa, dan Hermeneutika Kritis Adegan Titi Jagung yang merupakan catatan kritis atas tulisan saya.
1. Kekuatan Argumentatif dan Kedalaman Filosofis
Tulisan Erich menunjukkan kekuatan reflektif yang tinggi. Penulis tidak hanya mengkritisi klaim ADWA, tetapi juga mengajak pembaca untuk memahami hermeneutika secara lebih mendalam, khususnya melalui dua pendekatan Paul Ricoeur:
• Hermeneutika Kepercayaan: Di mana simbol dianggap sebagai wahana pewahyuan makna yang tulus.
• Hermeneutika Kecurigaan: Di mana simbol justru dipandang sebagai kedok yang menyembunyikan kepentingan kekuasaan.
Kritik terhadap ADWA sangat tajam karena menunjukkan bahwa pembacaan simbolik yang terlalu percaya justru berisiko menjadi alat legitimasi kekuasaan.
2. Kritik terhadap Gestur Politik dan Simbolisasi Kekuasaan
Erich berhasil membongkar ‘gestur bupati titi jagung’ sebagai ‘simbol politik yang tidak netral’. Ia menunjukkan bahwa:
• Gestur tersebut bukan sekadar ekspresi budaya, tetapi bagian dari strategi governmentality ala Foucault: seni memerintah melalui citra dan pengelolaan persepsi.
• Simbol politik seperti ini bisa menutupi realitas sosial yang lebih pahit, seperti ketimpangan ekonomi dan penderitaan pelaku ekonomi kecil (ibu-ibu jagung titi).
Ini adalah kritik yang sangat relevan dalam konteks politik lokal, di mana citra sering kali lebih penting daripada substansi kebijakan.
3. Bahasa Kritis dan Kontekstual
• Erich menggunakan bahasa yang tajam, reflektif, dan filosofis, namun tetap komunikatif.
• Referensi terhadap Sapardi Djoko Damono, Paul Ricoeur, dan Michel Foucault memperkuat legitimasi akademik tulisan.
• Kritik terhadap narasi Pemda dan media lokal menunjukkan keberanian intelektual dan kesadaran akan pentingnya ruang publik yang kritis.
4. Catatan
• Keseimbangan Tafsir: Meskipun hermeneutika kecurigaan penting, tulisan Erich cenderung menolak sepenuhnya kemungkinan makna positif dari simbol. Padahal, Ricoeur sendiri tidak menolak hermeneutika kepercayaan, melainkan mengusulkan dialektika antara keduanya.
• Kritik terhadap ADWA bisa lebih dialogis: Alih-alih hanya menolak, penulis bisa mengusulkan cara membaca ulang simbol titi jagung dengan pendekatan yang lebih reflektif dan partisipatif.
• Perlu data empirik: Misalnya, bagaimana dampak nyata lomba titi jagung terhadap pelaku ekonomi lokal? Apakah benar tidak ada perubahan? Kritik akan lebih kuat jika disertai bukti lapangan.
Tulisan ini adalah contoh cemerlang dari praktik hermeneutika kritis dalam ruang publik lokal. Ia mengajak kita untuk tidak larut dalam citra, tetapi berani membongkar makna tersembunyi di balik simbol kekuasaan.
Dalam konteks pendidikan politik dan pembentukan warga yang otonom, tulisan ini sangat relevan dan layak dijadikan bahan diskusi lintas bidang.
Sementara tulisan saya sangat sederhana, tanpa membela kepentingan siapa-siapa. Toh, saya BUKAN BAGIAN DARI BIROKRASI di Lembata. Juga bukan ANAK TANAH LEMBATA yang ‘wajib membela’ situasi di Tanah Lembata dengan ‘menikam seluruh jiwa’ untuknya.
Jika boleh, maka izinkanlah saya untuk ‘memberi catatan’ pada tulisan saya yang telah dibedah dengan sangat akademik oleh Erich Langobelen. Berikut catatan saya yang saya beri judul sederhana: Merayakan Simbol, Merawat Makna
1. Penghargaan terhadap Budaya Lokal
Tulisan saya mengangkat titi jagung dari perspektif sosiologis (dari perspektif keilmuan saya pada tataran reflektif) sebagai simbol identitas kolektif masyarakat Lamaholot. Saya hanya coba menunjukkan kepekaan budaya saya dengan menempatkan jagung sebagai “narasi hidup” yang menyatukan warga, bukan sekadar komoditas pangan. Saya memandang ini sebagai bentuk literasi budaya yang sangat penting dalam konteks otonomi daerah.
2. Narasi yang Hangat dan Humanis
Dalam semua tulisan saya, saya berusaha menggunakan gaya penulisan yang komunikatif dan menyentuh. Dengan itu, saya berusaha untuk tidak terjebak dalam jargon birokratis, melainkan menghadirkan narasi yang hidup, hangat, dan membumi. Kalimat seperti “ikut duduk di tikar, ikut memegang tongkol, ikut merasakan denyut kehidupan masyarakat” adalah metafora untuk melukiskan idealisme relasi antara negara dan rakyat. Di titik ini, tidak ada KEPENTINGAN YANG SAYA LAYANI. Justru di sinilah titik star untuk membangun sebuah ‘catatan kritis’ untuk Pemda Lembata dan masyarakat umumnya.
3. Hermeneutika sebagai Jembatan Makna
Dengan menyebut “titik hermeneutiknya”, saya hendak menunjukkan bahwa saya tidak sekadar mendeskripsikan peristiwa, tetapi juga MENGAJAK PEMBACA UNTUK MENAFSIRKAN MAKNA DI BALIK SIMBOL. Ini adalah pendekatan yang reflektif dan filosofis, sekaligus membumi. Dari perspektif Erich, hermeneutika dalam tulisan ini tidak elitis. Dan, memang saya tidak mau masuk ke wilayah itu. Yang mau saya tunjukkan adalah hal yang sangat sederhana, yakni hermeneutika sebagai ‘alat untuk memahami kehidupan sehari-hari masyarakat’.
Saya berangkat dari titik yang sangat sederhana. Namun, Erich berhasil ‘membuatnya menjadi yang sangat luar biasa’. Salut dan hormat terhadap keluar-biasaan akademik Erich.
4. Pembangunan sebagai Proses Sosial
Sederhananya, tulisan saya hendak menggeser paradigma pembangunan dari sekadar infrastruktur menuju relasi sosial dan kultural. Dalam tulisan saya, saya menegaskan bahwa pembangunan yang bermakna adalah yang menyentuh rasa, bukan hanya angka. INI ADALAH KRITIK HALUS NAMUN KUAT TERHADAP MODEL PEMBANGUNAN YANG TERLALU TEKNOKRATIS DAN JAUH DARI RAKYAT. Sekali lagi, di titik inilah, pertanyaan Erich tentang siapa yang saya layani, mungkin bisa terjawab. Tentu, dengan sedikit menunduk dan mengatup jemari di dada.
5. Kohesi Sosial sebagai Inti Otonomi
Dengan menyoroti interaksi antara ASN dan warga dalam lomba titi jagung, secara sederhana pula saya hendak menunjukkan bahwa OTONOMI DAERAH BUKAN HANYA TENTANG DESENTRALISASI KEKUASAAN, TETAPI TENTANG KEDEKATAN EMOSIONAL DAN SOSIAL ANTARA PEMERINTAH DAN RAKYAT. Dan, di titik ini pulalah terkandung KRITIK RINGAN terhadap Pemda Lembata. Ya…Boleh dipandang juga sebagai pelajaran penting bagi banyak daerah lain di Indonesia.
Menyulam Tradisi dan Pemerintahan
Ya…sekali lagi sederhananya, tulisan saya tersebut merupakan sebuah ‘jurnalisme reflektif yang menggabungkan narasi budaya, semangat lokal, dan pemikiran filosofis’ dengan cara yang amat sederhana dan mungkin jauh dari ranah akademis.
Saya hanya coba mengabarkan peristiwa dan menghidupkan makna. Dan, itulah gaya dan daya saya dalam menulis sebagai ‘bagian yang tak terpisahkan dari kerja diam jurnalisme saya’.
Namun, tak apalah. Catatan kritis Erich ‘membuka kesadaran’ saya bahwa tidak serampangan saja menulis di media massa. Butuh kuriositas yang mendalam. Mungkin di suatu saat nanti saya bisa memenuhi harapan Erich. Tentu tidak di media massa, tetapi di media yang lebih akademik!***