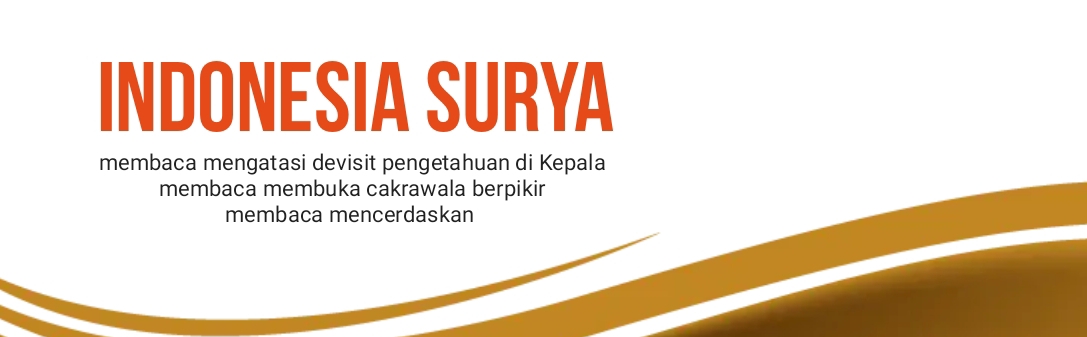Nusa Tenggara Timur masih sering diberitakan sebagai provinsi termiskin di Indonesia, dan narasi itu sudah begitu lama menempel hingga menjadi semacam label yang sulit dilepas, seolah-olah kemiskinan adalah identitas bawaan yang tidak bisa diubah.
Padahal di balik angka-angka statistik yang dingin, ada masyarakat yang bekerja keras setiap hari, ada petani yang bertahan dengan lahan kering, ada nelayan yang menantang laut demi hidup yang lebih baik.
Sayangnya, suara mereka jarang terdengar, karena narasi yang lebih kuat justru datang dari luar dari sudut pandang yang memotret NTT sebagai wilayah yang kasihan, bukan wilayah yang berdaya.
Sebagai mahasiswa Ilmu Komunikasi sekaligus bagian dari masyarakat NTT, saya belajar bahwa kemiskinan tidak hanya soal kurangnya uang atau sumber daya, tetapi juga soal bagaimana komunikasi dibangun antara pemerintah, masyarakat, dan media.
Ketika komunikasi pembangunan berjalan satu arah, dari atas ke bawah, banyak kebijakan yang gagal dipahami, dan akhirnya tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di akar rumput.
Informasi tentang program bantuan sering hanya berputar di tingkat elite, sementara warga desa yang paling membutuhkan justru tidak tahu cara mengaksesnya.
Media juga punya peran besar dalam membentuk persepsi publik tentang NTT.
Terlalu sering berita tentang daerah ini hanya menyoroti bencana, kekeringan, dan kemiskinan, tanpa memberi ruang bagi kisah tentang inovasi, solidaritas, dan ketahanan masyarakatnya.
Padahal, di banyak kampung ada anak muda yang menggerakkan koperasi, perempuan yang membangun usaha kecil, dan komunitas yang mengelola air bersih secara mandiri—cerita-cerita seperti inilah yang bisa mengubah cara kita memandang kemiskinan.
Mengubah narasi berarti menggeser cara bicara: dari belas kasihan menuju kolaborasi.
Kita tidak lagi menempatkan masyarakat miskin sebagai objek bantuan, tetapi sebagai subjek yang punya kemampuan dan gagasan untuk maju bersama.
Dalam kerangka ini, komunikasi menjadi jembatan—menghubungkan niat baik pemerintah, daya juang masyarakat, dan dukungan dari berbagai pihak yang ingin berkontribusi. Mahasiswa komunikasi di NTT punya tanggung jawab moral untuk ikut membangun narasi baru ini. Melalui media sosial, video pendek, atau liputan komunitas, kita bisa menampilkan wajah lain dari NTT—wajah yang penuh semangat, kerja keras, dan harapan.
Dengan cerita-cerita positif yang jujur, publik luar akan melihat bahwa NTT bukan sekadar provinsi miskin, melainkan provinsi yang sedang berjuang bangkit dengan caranya sendiri. Kemiskinan memang nyata, tetapi ia bukan takdir. Yang perlu kita ubah adalah cara kita berbicara tentangnya—karena dari komunikasi yang menghargai, kolaborasi akan tumbuh, dan dari kolaborasi itulah masa depan NTT bisa berubah.