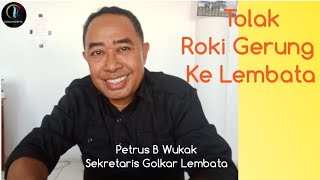Isu kekerasan seksual di Nusa Tenggara Timur (NTT) kini menjadi salah satu krisis sosial paling serius yang menodai wajah kemanusiaan di daerah tersebut.
Di tengah citra NTT sebagai provinsi dengan kekayaan budaya, ketaatan religius, dan semangat kekeluargaan yang tinggi, tersembunyi kenyataan pahit bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak justru terjadi dengan frekuensi yang mencengangkan.
Data menunjukkan bahwa sekitar 75 persen narapidana di NTT adalah pelaku kekerasan seksual. Angka ini tidak hanya mencerminkan tingginya tingkat kejahatan seksual, tetapi juga menunjukkan kerusakan moral dan kegagalan sistem perlindungan sosial di tingkat keluarga, masyarakat, dan negara. Bahkan, sebagian besar pelaku adalah orang-orang terdekat korban—ayah, guru, paman, suami, atau tetangga—yang seharusnya menjadi pelindung justru berubah menjadi predator.
Fakta ini memperlihatkan bahwa kekerasan seksual di NTT bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan gejala sosial yang mengakar dalam struktur budaya dan ketimpangan sosial yang mendalam.
Salah satu faktor utama yang melatarbelakangi maraknya kekerasan seksual di NTT adalah kemiskinan dan ketimpangan pendidikan. Di banyak wilayah pedesaan, anak-anak perempuan tumbuh dalam kondisi ekonomi yang sulit, dengan akses terbatas terhadap pendidikan dan informasi tentang hak-hak mereka.
Kemiskinan menciptakan ketergantungan ekonomi yang besar terhadap laki-laki atau orang yang lebih berkuasa, dan situasi ini sering kali dimanfaatkan oleh pelaku untuk menekan atau mengendalikan korban.
Dalam kondisi seperti ini, korban jarang berani melapor karena takut kehilangan sumber penghidupan atau mengalami stigma sosial.
Selain itu, budaya patriarki yang masih kuat di sebagian masyarakat NTT menjadikan perempuan dan anak perempuan berada dalam posisi yang lemah. Mereka sering dipandang sebagai pihak yang harus tunduk, diam, dan menjaga kehormatan keluarga, bahkan jika mereka menjadi korban kekerasan.
Akibatnya, banyak kasus diselesaikan secara adat atau kekeluargaan, bukan melalui jalur hukum formal, yang pada akhirnya menutup jalan keadilan bagi korban.
Faktor geografis juga turut memperparah keadaan. NTT terdiri dari ratusan pulau dengan akses transportasi dan komunikasi yang terbatas, sehingga korban di daerah terpencil sulit menjangkau lembaga perlindungan atau aparat hukum.
Keterbatasan layanan psikologis dan pendampingan hukum membuat korban sering kali harus menghadapi trauma seorang diri. Di beberapa kasus, korban bahkan justru menjadi pihak yang disalahkan.
Ironisnya, terdapat kasus di mana oknum aparat kepolisian yang seharusnya melindungi malah menjadi pelaku pelecehan terhadap korban yang datang melapor.
Hal ini memperlihatkan betapa rapuhnya sistem keadilan di NTT. Ketika lembaga penegak hukum sendiri menjadi bagian dari masalah, maka sulit diharapkan ada kepercayaan publik terhadap proses hukum. Situasi ini semakin menegaskan bahwa kekerasan seksual di NTT adalah persoalan sistemik yang membutuhkan pembenahan menyeluruh, bukan sekadar hukuman terhadap individu pelaku.
Dampak kekerasan seksual terhadap korban sangat mendalam, terutama bagi anak-anak. Trauma psikologis, depresi, kecemasan, hingga kehilangan rasa percaya diri menjadi beban yang sulit disembuhkan.
Banyak korban yang akhirnya putus sekolah, kehilangan semangat hidup, bahkan menolak berinteraksi dengan lingkungan sosial. Mereka menanggung rasa malu yang seharusnya menjadi beban pelaku. Dalam masyarakat yang masih mengedepankan stigma, korban sering kali dipandang sebagai “aib” keluarga. Akibatnya, korban tidak hanya menderita akibat kekerasan itu sendiri, tetapi juga karena penolakan dan pengucilan dari lingkungan.
Di tingkat sosial, fenomena ini menyebabkan luka kolektif: masyarakat kehilangan rasa aman, keluarga kehilangan kepercayaan, dan nilai-nilai kemanusiaan tereduksi oleh diamnya banyak pihak terhadap kekerasan yang terjadi di sekitar mereka.
Sementara itu, dari perspektif pembangunan manusia, kekerasan seksual adalah penghambat besar bagi kemajuan NTT. Provinsi ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti kemiskinan, stunting, dan keterbatasan pendidikan. Jika perempuan dan anak-anak—sebagai aset masa depan daerah—hidup dalam ketakutan dan trauma, maka pembangunan tidak akan pernah berakar kuat.
Sebuah daerah tidak bisa disebut maju apabila tubuh dan jiwa warganya terus diteror oleh kekerasan.
Pemerintah memang telah memiliki dasar hukum yang kuat, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), tetapi penerapannya di lapangan masih jauh dari efektif.
Banyak aparat yang belum memiliki pemahaman dan sensitivitas terhadap isu kekerasan seksual, sementara lembaga pendamping korban masih kekurangan sumber daya manusia dan dana.
Lebih dari itu, budaya diam menjadi musuh terbesar dalam upaya pemberantasan kekerasan seksual di NTT. Banyak keluarga memilih menutupi kasus karena takut “nama baik” mereka rusak. Beberapa tokoh adat atau agama bahkan menyarankan penyelesaian damai, seolah kekerasan seksual hanyalah “masalah keluarga” yang tidak perlu diproses secara hukum.
Pandangan ini berbahaya karena menciptakan impunitas dan memberi pesan bahwa pelaku bisa lolos dari tanggung jawab. Di sisi lain, media massa lokal dan lembaga masyarakat sipil sering kali menjadi satu-satunya pihak yang berani mengangkat isu ini ke publik. Namun, kerja mereka sering terbatas karena kurangnya dukungan dari pemerintah dan aparat hukum. Padahal, peran media dan masyarakat sipil sangat penting untuk mengubah kesadaran kolektif bahwa kekerasan seksual adalah kejahatan, bukan sekadar skandal pribadi.
Penulis berpandangan bahwa penyelesaian masalah kekerasan seksual di NTT harus dimulai dari keberanian moral untuk mengakui bahwa ini adalah krisis kemanusiaan, bukan hanya pelanggaran hukum.
Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa layanan pelaporan dan perlindungan korban tersedia di setiap kabupaten, termasuk wilayah pedalaman.
Akses terhadap pendampingan hukum, psikologis, dan medis harus dijamin oleh negara tanpa diskriminasi. Aparat penegak hukum perlu dilatih agar memiliki perspektif korban (victim-centered approach) dan tidak lagi memperlakukan korban sebagai tersangka.
Selain itu, pendidikan tentang seksualitas, kesetaraan gender, dan perlindungan anak harus diperkenalkan sejak dini di sekolah dan komunitas, agar generasi muda NTT tumbuh dengan kesadaran bahwa tubuh dan martabat manusia tidak boleh dilanggar dalam bentuk apa pun.
Dalam masyarakat yang religius seperti NTT, lembaga keagamaan juga memiliki tanggung jawab moral untuk terlibat aktif. Gereja, masjid, dan lembaga adat seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi korban, bukan arena penghakiman. Mereka perlu mengajarkan empati, pengampunan yang benar, dan keadilan yang berpihak pada korban. Kolaborasi lintas sektor sangat penting: pemerintah, lembaga agama, sekolah, media, dan organisasi masyarakat harus bekerja bersama untuk membangun ekosistem perlindungan sosial yang kuat.
Di sisi lain, masyarakat juga perlu berani membongkar budaya patriarki dan sikap pasif terhadap kekerasan. Diam di tengah penderitaan korban adalah bentuk keterlibatan tidak langsung dalam kejahatan itu sendiri.
Kita tidak boleh lupa bahwa setiap angka dalam statistik kekerasan seksual di NTT merepresentasikan manusia dengan cerita, rasa sakit, dan harapan yang hancur.
Korban-korban itu bukan sekadar data dalam laporan, melainkan bagian dari kita—anak-anak, saudara, teman, bahkan tetangga. Maka, isu ini harus diperlakukan dengan keseriusan yang sama seperti menghadapi bencana alam, karena kekerasan seksual adalah bencana moral yang menggerogoti fondasi kemanusiaan.
Pemerintah pusat dan daerah perlu menjadikan NTT sebagai prioritas dalam kebijakan nasional perlindungan perempuan dan anak, dengan fokus pada rehabilitasi korban, penegakan hukum tegas, dan pencegahan berbasis pendidikan.
Pada akhirnya, perubahan tidak akan datang hanya dari undang-undang atau aparat hukum, tetapi dari kesadaran kolektif masyarakat NTT sendiri.
Setiap keluarga, sekolah, tokoh adat, dan pemimpin agama harus menjadi benteng pertama dalam melindungi perempuan dan anak dari kekerasan. Saat masyarakat berani bersuara, mendukung korban, dan menolak budaya diam, maka kejahatan ini akan kehilangan ruang untuk tumbuh.
Harapan penulis, NTT suatu hari akan dikenal bukan lagi sebagai provinsi dengan angka kekerasan seksual tertinggi, tetapi sebagai daerah yang berhasil bangkit dengan solidaritas kemanusiaan.
Provinsi yang menempatkan perempuan dan anak pada posisi paling aman, paling dihargai, dan paling dilindungi. Sebab sejatinya, ukuran kemajuan sebuah daerah tidak ditentukan oleh angka ekonomi atau infrastruktur, melainkan oleh sejauh mana masyarakatnya mampu menjaga martabat manusia dari segala bentuk kekerasan.