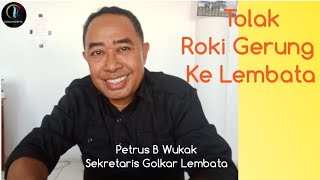Tulisan Gregorius Duli Langobelen berjudul “Wajah Simbolik Jabatan: Bahasa, Kuasa, dan Hermeneutika Kritis Adegan Titi Jagung” (https://fajarpedia.com/2025/10/12/wajah-simbolik-jabatan-bahasakuasa-dan-hermeneutika-kritis-adegan-titi-jagung/) sebagai tanggapan atas tulisan dari Anselmus Dore Woho Atasoge (ADWA) yang berjudul “Hermeneutik ‘Titi Jagung’ dan Wajah Otonomi yang Membumi”, bagi penulis adalah undangan untuk berdialog.
Ia membuka ruang kritik yang penting, khususnya terhadap cara kita memahami hubungan antara bahasa, simbol, dan kekuasaan. Namun, saya merasa perlu menanggapi, bukan untuk meniadakan kecurigaan yang diajukan Gregorius, melainkan untuk mengembalikannya ke dalam konteks hermeneutik yang lebih seimbang dan manusiawi.
Hermeneutika: Dari Kecurigaan ke Dialog
Gregorius menuduh tulisan Anselmus berhenti pada “hermeneutika kepercayaan” dan karenanya dangkal.
Ia mengutip Paul Ricoeur dan menegaskan pentingnya “hermeneutika kecurigaan”. Benar bahwa Ricoeur—bersama Marx, Freud, dan Nietzsche—menghidupkan tradisi hermeneutik kritis yang mengungkap struktur tersembunyi di balik ideologi. Namun Gregorius tampaknya membaca Ricoeur secara separuh hati.
Ricoeur sendiri menolak dikotomi hitam-putih antara kepercayaan dan kecurigaan. Dalam Freud and Philosophy (1970), ia menulis bahwa tugas hermeneutika bukan hanya membongkar ilusi, tetapi juga memulihkan makna setelah kecurigaan bekerja. Dengan kata lain, penafsiran yang matang bukan berhenti pada pembongkaran, melainkan menemukan kembali dimensi kepercayaan yang telah disaring oleh kritik.
Kecurigaan tanpa pemulihan adalah skeptisisme yang mandul; pemulihan tanpa kritik adalah naivitas. Keduanya harus bersuara bersama. Maka hemat penulis, pembacaan Anselmus terhadap Titi Jagung sebagai “wajah otonomi yang membumi” tidak dimaksudkan sebagai pengagungan simbol, tetapi sebagai upaya memahami bagaimana simbol dan tindakan sosial bekerja di dalam ruang kebersamaan masyarakat.
Penulis melihat Anselmus tidak sedang menutup mata terhadap kuasa, tetapi sedang mencoba melihat apa yang sungguh-sungguh terjadi di ruang sosial itu.
Kekuasaan Tidak Selalu Represif
Gregorius mengajukan tafsir Foucauldian tentang governmentality, yakni kekuasaan yang bekerja halus membentuk kesadaran warga. Ia membaca adegan bupati memipil jagung sebagai siasat kuasa—drama yang menaturalisasi mitos “pemimpin merakyat”. Pandangan ini tajam, tapi juga berisiko menafsir semua tindakan sosial sebagai manipulasi.
Michel Foucault sendiri tidak memandang kekuasaan hanya sebagai represi.
Dalam The History of Sexuality, Vol. I, ia menulis bahwa kekuasaan “tidak hanya menindas, tetapi juga produktif; ia menghasilkan realitas, memunculkan wacana, dan menciptakan subjek.” Artinya, praktik sosial seperti Titi Jagung bisa menjadi medan produktif di mana warga, ASN, dan pemimpin bersama-sama memproduksi makna kebersamaan. Ia tidak otomatis menjadi “manipulasi kekuasaan”, melainkan bisa menjadi teknologi sosial yang memperkuat rasa komunitas dan kohesi sosial.
Kritik Gregorius, meski tajam, gagal membaca potensi produktif dari tindakan simbolik ini. Ia hanya melihat relasi dominasi, bukan kemungkinan transformasi melalui perjumpaan simbolis.
Ritual, Solidaritas, dan Realitas Sosial
Sosiologi klasik mengajarkan bahwa ritual bukanlah ruang tipuan. Émile Durkheim dalam The Elementary Forms of Religious Life (1912) menyebut bahwa dalam ritual, masyarakat “menyembah dirinya sendiri” — bukan dalam arti egoistis, tetapi sebagai cara membangun kesadaran kolektif.
Demikian pula Victor Turner (1969) menjelaskan bahwa setiap ritual mengandung momen communitas — keadaan sementara di mana perbedaan sosial mencair dan solidaritas lahir dari pengalaman bersama.
Dalam lomba titi jagung, kita melihat pegawai, ibu-ibu, dan warga duduk sama rendah, tertawa sama lepas. Ia mungkin sederhana, bahkan terlihat sepele. Tapi di situlah justru terletak kekuatan simbolnya: ia menciptakan ruang sosial yang manusiawi di tengah birokrasi yang sering kaku.
Gregorius membaca itu sebagai “drama kuasa”. Saya membaca sebagai “drama kemanusiaan”. Dua tafsir yang sah, tetapi saya memilih yang lebih memberi ruang bagi harapan sosial.
Batas Kritik dan Etika Membaca
Gregorius menuduh tulisan Anselmus “melegitimasi kebijakan keliru dan citra penguasa.” Tuduhan ini terlalu jauh.
Kritik adalah penting, tetapi ia membutuhkan etik membaca (ethics of reading). Dalam tradisi hermeneutik Gadamerian, pemahaman sejati terjadi ketika “horison pembaca” dan “horison teks” berjumpa (fusion of horizons). Dalam konteks ini, teksnya adalah tindakan sosial warga; maka kita harus mendengar dari dalam, bukan hanya menilai dari luar.
Kritik akademik yang hanya memakai lensa teori, tanpa mendengarkan pengalaman pelaku lokal, akan kehilangan sentuhan kemanusiaannya. Begitu juga membaca peristiwa sosial tanpa mendengarkan pengalaman subjek di dalamnya warga yang memipil jagung, ASN yang ikut membantu, ibu-ibu yang tertawa sambil bernyanyi berarti meniadakan horison lokal. Hermeneutika yang hanya mencurigai tanpa mendengarkan berisiko menjadi kolonial terhadap makna lokal.
Kita memerlukan apa yang disebut Clifford Geertz (1973) sebagai thick description—deskripsi tebal yang tidak hanya melihat struktur, tetapi juga makna yang dirasakan. Tanpa itu, kritik menjadi generalisasi kosong. Titi Jagung bukan hanya peristiwa simbolik di atas panggung kekuasaan; ia adalah bagian dari bahasa sehari-hari masyarakat Lembata—bahasa tentang kerja sama, syukur, dan kebersamaan setelah panen. Kalau semua itu langsung dibaca sebagai “manipulasi”, kita justru menutup kemungkinan memahami cara orang lokal membangun solidaritas.
Simbol dan Tindakan Performatif
Gregorius memandang simbol sebagai kedok yang menutupi realitas. Saya justru berpijak pada teori tindakan performatif J.L. Austin (1962): bahwa kata dan tindakan bisa melakukan sesuatu. Ketika bupati duduk bersama warga dan ikut titi jagung, tindakan itu tidak hanya menandai “keakraban”—ia menciptakan keakraban itu.
Dalam teori performativitas, simbol memiliki daya konstitutif: ia membentuk kenyataan sosial yang baru. Apakah tindakan itu bisa juga berpotensi politis? Tentu saja. Tetapi politik tidak selalu berarti manipulasi; politik juga bisa berarti penciptaan ruang kebersamaan yang lebih manusiawi.
Kita tentu boleh curiga. Tapi kalau setiap gerak tangan pemimpin, setiap sapaan, setiap simbol budaya langsung kita curigai sebagai manipulasi, maka masyarakat akan kehilangan ruang simbolik untuk saling percaya. Kita akan hidup dalam masyarakat tanpa makna.
Dari Kecurigaan ke Rekonsiliasi Sosial
Gregorius mengakhiri tulisannya dengan kalimat tegas: “Tidak ada adegan yang netral; setiap gestur adalah medan perebutan makna dan kekuasaan.” Saya sepakat. Tetapi jika setiap gestur hanya dibaca sebagai perebutan kuasa, maka tak ada lagi ruang bagi rekonsiliasi sosial.
Masyarakat tidak hidup dari kecurigaan semata; mereka hidup dari perjumpaan. Dalam konteks Lembata, titi jagung bukan hanya simbol ekonomi agraris, melainkan juga bahasa solidaritas. Bahasa ini memungkinkan warga yang lelah oleh birokrasi untuk sekali waktu duduk bersama—mendekat, bukan menjauh.
Pierre Bourdieu mengingatkan bahwa symbolic power memang bisa meneguhkan hegemoni, tapi juga dapat memberi legitimasi sosial yang membangun kesepakatan bersama. Kekuasaan simbolik tidak hanya menipu; ia juga memampukan masyarakat membentuk konsensus baru.
Penutup: Hermeneutika yang Membumi
Hermeneutika yang membumi bukan berarti menutup mata terhadap kuasa, melainkan menolak reduksionisme. Ia membaca tanda dengan kesadaran kritis sekaligus hati yang terbuka terhadap makna lokal.
Dalam konteks ini, Titi Jagung adalah ruang di mana negara dan masyarakat saling mendekat. Ia memang bisa disusupi makna politis, tapi ia juga memberi kesempatan bagi warga untuk melihat pejabat sebagai manusia biasa.
Titi Jagung, bagi saya, tetap merupakan simbol otentik perjumpaan antara negara dan masyarakat, antara birokrasi dan budaya. Ia bisa disusupi makna politik, tetapi tidak bisa dipenjarakan oleh kecurigaan tunggal. Di situlah letak kekuatan simbolnya: ia membumikan kekuasaan.
Sebagaimana diingatkan Ricoeur, tugas penafsir adalah “to suspect in order to restore” — mencurigai untuk memulihkan, Maka tugas kita bukan hanya membongkar makna yang tersembunyi, tetapi juga menyembuhkan makna yang terluka . Itulah jalan tengah yang membedakan hermeneutika dari sinisme.
Saya tidak menulis ini untuk meniadakan kritik Gregorius, melainkan untuk melengkapinya. Kritik tanpa empati akan tumpul, empati tanpa kritik akan buta. Di antara keduanya, kita perlu hermeneutika yang lebih manusiawi—yang curiga tapi tetap percaya, yang kritis tapi tidak sinis.
Maka, alih-alih menenggelamkan makna Titi Jagung dalam lumpur kecurigaan, marilah kita memeliharanya sebagai ruang simbolik tempat birokrasi belajar rendah hati dan rakyat belajar percaya kembali. Di sanalah otonomi menemukan maknanya yang paling sederhana, sekaligus paling dalam: otonomi yang berakar, yang membumi, yang manusiawi. ***