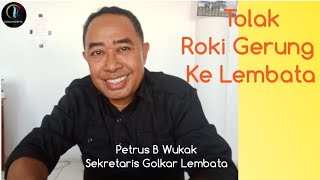Tentang Ajakan Membaca Anatomi Politik
Gregorius Duli Langobelen (GDL) dalam tulisannya “Teks, Konteks, dan Risiko Hipokrisi: Ajakan Tidak Menjadi Dangkal Dua Kali” (https://fajarpedia.com/2025/10/14/tekskonteksdan-resiko-hipokrisiajakan-menjadi-dangkal-dua-kali/) memulai dengan klaim moral bahwa ia berpihak pada “kelompok paling rentan”, yakni ibu-ibu pelaku ekonomi titi jagung. Klaim ini tampak mulia, tetapi segera memperlihatkan bias metodologis yang serius: ia mengasumsikan relasi kuasa yang kaku dan tak terbantahkan — seolah masyarakat selalu korban dan pemerintah selalu pelaku.
Sikap seperti ini lebih menyerupai populisme moral daripada pembacaan ilmiah yang proporsional. Sebagai direktur lembaga riset (Tenapulo Research), GDL semestinya tahu bahwa keberpihakan tanpa data empiris hanya melahirkan dogma. Ia mengutip penderitaan ibu-ibu di Bogemart tanpa menunjukkan bukti riset lapangan, wawancara, atau data ekonomi rumah tangga. Empati yang semestinya menjadi pintu analisis justru berubah menjadi slogan.
Tulisan saya sebelumnya justru menolak reduksi semacam itu. Saya membaca simbol titi jagung bukan sebagai permainan kuasa belaka, tetapi sebagai ruang sosial yang hidup di mana makna dinegosiasikan antara warga dan pemerintah. Itu bukan sikap “menutup mata”, melainkan upaya menjaga keseimbangan antara kecurigaan dan pemulihan. Di titik inilah GDL mulai kehilangan konsistensi akademiknya: ia menolak “kedangkalan hermeneutik kepercayaan” tapi jatuh pada reduksionisme hermeneutik kecurigaan — kecurigaan yang berhenti pada dirinya sendiri.
Tentang Membedah Kegagalan Hermeneutis
GDL menuduh saya dan Anselmus D.W. Atasoge gagal memahami hermeneutika kecurigaan ala Ricoeur. Ironisnya, justru ia sendiri yang membaca Ricoeur secara parsial. Ia berhenti pada tahap mistrust dan lupa melangkah ke tahap restoration of meaning — padahal tahap itulah inti dari hermeneutika Ricoeur.
Kritiknya terhadap saya yang dianggap “kontradiktif” (karena menolak reduksionisme tapi tetap kritis pada kuasa) memperlihatkan ketidaktelitiannya membaca teks. Ricoeur memang memadukan curiga dan percaya sebagai dialektika, bukan oposisi biner. Ketika saya menulis “curiga tapi tetap percaya”, saya sedang menggemakan prinsip Ricoeur yang paling esensial: bahwa makna hanya pulih setelah dicurigai.
GDL yang berlatar belakang riset seharusnya mampu membaca konteks teoretik sebelum menghakimi. Dalam tulisan-tulisannya yang lain, GDL kerap memakai pendekatan “disequilibrium epistemik”—menyerang tanpa membangun jembatan dialog. Maka, ketika ia menuduh orang lain “sinis”, tudingan itu seperti cermin yang memantulkan dirinya sendiri.
Tentang Siapa yang Menang dan Siapa yang Kalah
GDL bertanya, “siapa yang akan menang dalam perebutan makna — bupati atau ibu-ibu?” Pertanyaan ini menunjukkan kesalahan mendasar dalam logika hermeneutiknya: ia memaksakan dikotomi politik di dalam ruang simbolik yang justru cair.
Dalam pandangan hermeneutika sosial, makna tidak dimenangkan, tetapi dinegosiasikan. Gestur bupati memang bukan bebas nilai, tetapi juga bukan penindasan total. Warga memiliki kapasitas untuk memberi tafsir tandingan, media dapat mengintervensi, publik bisa menafsir ulang citra pejabat.
GDL gagal membaca dinamika ini karena kerangka pikirnya tertutup oleh paradigm “strukturalisme curiga”—semuanya harus di bawah-bawah, tertindas, dan kalah. Padahal, jika ia benar-benar berpihak pada masyarakat, ia harus memberi ruang bagi agensi subaltern untuk berbicara sendiri — bukan mengatasnamakan mereka. Ironisnya, dalam mengkritik “ventriloquism pejabat”, GDL justru menjadi ventriloquist baru yang berbicara atas nama “ibu - ibu” tanpa menghadirkan suara otentik mereka.
Tentang Belantara Filsafat dan Depolitisasi Wacana
Pada bagian tengah tulisannya, GDL menyerang saya karena dianggap “terjebak dalam belantara filsafat tanpa arah.” Tuduhan ini justru berbalik arah. Saya memakai filsafat secara komunikatif — menghubungkan Ricoeur, Durkheim, Turner, dan Bourdieu untuk menjelaskan realitas sosial Lembata.
Sebaliknya, GDL menggunakan nama-nama besar (Spivak, Foucault, Derrida) sebagai perisai otoritas, bukan alat dialog. Ia menulis seolah filsafat adalah tembok, bukan jembatan. Padahal, dalam diskursus sosial, teori seharusnya membuka percakapan antara pengalaman lokal dan horizon global. Ketika teori berubah jadi benteng, ia kehilangan etikanya: ia berhenti mendengarkan manusia di balik teks.
Secara metodologis, GDL juga tergelincir: ia mengabaikan konteks empiris yang semestinya menjadi fokus seorang peneliti sosial. Ia membangun kesimpulan moral tanpa observasi, mengutip Spivak tanpa menelusuri konteks kolonial yang melahirkan istilah “subaltern,” dan menyebut “epistemic violence” tanpa mendengar bagaimana ibu-ibu titi jagung memaknai pengalaman mereka sendiri.
Dengan begitu, tulisan yang mengaku “pro-subaltern” justru melakukan kekerasan epistemik baru — mematikan suara rakyat dengan jargon akademik yang tak terhubung pada kenyataan.
Tentang Risiko Hipokrisi dan Jalan Sunyi Subaltern
GDL menuduh saya “hipokrit” karena mengusulkan hermeneutika yang “curiga tapi percaya.” Tapi siapa sebenarnya yang hipokrit? Saya konsisten sejak awal: saya tidak menolak kritik, tapi ingin mengembalikannya ke ruang dialog.
Sebaliknya, GDL dalam tulisannya sendiri sebelumnya (Wajah Simbolik Jabatan) menyerukan agar pemerintah “reflektif dan terbuka pada evaluasi,” tetapi kini menutup pintu dialog dengan menstempel lawan pikirnya sebagai “naif, dangkal, dan kolonial.” Secara akademik, ini inkonsisten. Secara etis, ini manipulatif.
Dalam ruang wacana publik, konsistensi lebih penting daripada superioritas teoretik.
Kalau setiap tanggapan terhadap kritiknya dianggap pembela kekuasaan, maka GDL bukan sedang berdiskursus, melainkan sedang mengamankan ideologinya sendiri.
Sebagai direktur lembaga riset, ia seharusnya mendorong “verifikasi sosial”, bukan “deklarasi moral.” Riset yang baik tidak berhenti pada mencurigai, tetapi juga memulihkan — sebagaimana prinsip Ricoeur yang ia klaim kuasai, tapi tidak ia praktikkan.
Tentang Subaltern, Ventriloquism, dan Epistemic Violence
Di bagian akhir, GDL mengutip Spivak dengan penuh dramatika: “Can the Subaltern Speak?” untuk menggambarkan ibu-ibu titi jagung sebagai pihak yang tak bisa bersuara.
Lagi-lagi, pembacaan ini cacat konteks.
Spivak berbicara tentang kolonialisme epistemik global, bukan relasi simbolik antara bupati dan warga di Lembata. Mengimpor teori poskolonial dalam skala mikro tanpa adaptasi konseptual hanya akan menyederhanakan Spivak. Apalagi jika “subaltern” yang dimaksud masih bisa berinteraksi, berdagang, dan diwawancara, maka mereka bukan subaltern yang bisu, tetapi agen sosial yang aktif.
Dengan demikian, GDL tidak sedang membela suara rakyat, tetapi sedang memonopoli representasi rakyat. Ironisnya, inilah bentuk epistemic violence yang justru ia tuduhkan kepada pejabat.
Risiko Hipokrisi yang Sesungguhnya
GDL menutup tulisannya dengan ajakan moral agar kita “tidak dangkal dua kali.”
Ajakan itu terdengar luhur, tetapi berbalik arah: sebab dalam setiap peringatan moral yang menolak kritik, tersembunyi ketakutan untuk berdialog dengan yang berbeda.
Kedangkalan yang sesungguhnya bukanlah gagal memahami konteks, melainkan takut menerima tafsir lain. Hermeneutika yang sehat seharusnya berani salah, berani didengar, dan berani mendengar. Namun GDL memilih posisi hakim, bukan pembaca.
Hermeneutika yang lupa pulang adalah hermeneutika yang berhenti di menara gading teori — sibuk menuduh, lupa menyapa manusia.
Menutup dengan Cermin
Saya menulis ini bukan untuk memenangkan debat, tetapi untuk mengingatkan bahwa filsafat tanpa kerendahan hati adalah bentuk baru dari arogansi. Hermeneutika yang sehat tidak menyingkirkan kuasa, tapi juga tidak mengabaikan manusia di balik kuasa.
Jika GDL ingin mengajak kita agar “tidak dangkal dua kali,” maka izinkan saya menambahkan satu ajakan lagi: janganlah kita takut untuk menjadi dalam sekali — sampai menemukan diri kita yang juga keliru.
Karena pada akhirnya, semua tafsir, termasuk tafsir saya dan GDL, hanyalah jalan berliku menuju satu hal yang sama: kejujuran untuk mendengarkan manusia, bukan menaklukkannya lewat teori.