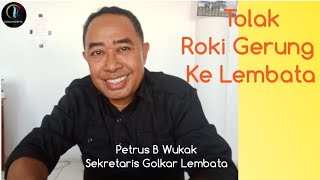Dalam perdebatan panjang tentang tafsir simbolik Titi Jagung di Lembata, Gregorius Duli Langobelen (GDL) dalam tulisannya (https://fajarpedia.com/2025/10/15/kemunduran-ideologis-ketika-igo-mengajak-tenggelam-di-kolam-yang-dangkal/) kembali mengajukan kritik tajam terhadap tulisan saya dan Anselmus DW Atasoge (ADWA). Ia menuduh bahwa kami “melemah positioning,” “terjebak dalam normalisasi gestur kekuasaan,” “lompat teori tanpa arah,” dan “mengajak tenggelam di kolam dangkal.”
Saya menulis tanggapan ini bukan untuk menang debat, tetapi untuk meneguhkan integritas posisi hermeneutik yang saya yakini: bahwa membaca simbol budaya lokal harus dilakukan dengan keseimbangan antara kecurigaan kritis dan pemulihan makna. Hermeneutika yang sehat tidak berhenti di tahap membongkar, tetapi bergerak menuju pemulihan—memberi ruang bagi warga untuk menafsir sendiri, bukan sekadar menjadi objek tafsir para elite.
Membaca Ulang Awal Argumen GDL: Kutipan Bourdieu dan Kelemahan Empirisnya
Tulisan GDL dibuka dengan kutipan Bourdieu: “Ketenangan sosial sering kali adalah tanda ketidakberdayaan, bukan keadilan.”
Secara retoris, ini pembuka yang kuat. Ia ingin menegaskan bahwa kedamaian simbolik—seperti yang ia lihat dalam praktik Titi Jagung—tidak boleh diterima begitu saja sebagai tanda keadilan.
Namun, kutipan besar tanpa konteks empiris cenderung menjadi senjata ideologis ketimbang pisau analisis. Kedamaian sosial memang bisa berfungsi sebagai penutup ketidakadilan, tetapi tidak selalu demikian. Pesta panen, titi jagung, atau gotong royong bisa pula menjadi ruang perjumpaan warga yang jujur—tak seluruhnya diatur oleh kuasa.
Jika GDL menyamakan semua “kedamaian simbolik” sebagai topeng kekuasaan, ia justru menutup ruang bagi makna lokal yang hidup.
“Kolam Dangkal” dan Dogma Kecurigaan
GDL menuduh kami “terjebak pada normalisasi gestur kekuasaan” dan hanya membaca lapisan permukaan—senyum, tawa, kebersamaan—tanpa menembus makna terdalam. Ia menegaskan bahwa hermeneutika sejati harus selalu mencurigai semua jawaban permukaan.
Masalahnya, GDL tidak menunjukkan satu pun data empiris di Lembata yang mendukung generalisasi itu. Kecurigaan epistemik adalah alat, bukan tujuan. Tanpa data, ia menjadi dogma kecurigaan—mengulang kata “kuasa” tanpa menjelaskan bagaimana kuasa itu bekerja secara konkret.
Hermeneutika kritis bukanlah penolakan atas simbol, melainkan upaya memahami simbol secara mendalam dan kontekstual. Sebab, sebagaimana saya tulis sebelumnya: “Kecurigaan tanpa pemulihan adalah skeptisisme; pemulihan tanpa kritik adalah naivitas.”
Antara Kecurigaan dan Pemulihan: Ricoeur dan Jalan Tengah Hermeneutika
Saya tetap memegang prinsip Paul Ricoeur: curiga tapi percaya. Kecurigaan epistemik perlu untuk menyingkap struktur kuasa tersembunyi, tetapi kepercayaan hermeneutik dibutuhkan untuk membangun kembali makna bersama.
Jika GDL menjadikan curiga sebagai imperatif tunggal, ia kehilangan dimensi pemulihan. Padahal tugas hermeneutika bukan hanya membongkar topeng, melainkan menautkan simbol pada kehidupan sosial yang lebih adil.
Simbol seperti Titi Jagung tidak selalu menjadi alat legitimasi kekuasaan. Ia bisa menjadi tindakan performatif (Austin) yang menciptakan realitas sosial baru, communitas (Turner) yang memperkuat solidaritas, sekaligus ruang negosiasi makna antara warga dan pejabat.
Tuduhan “Lompat Teori” dan Soal Konsistensi Akademik
GDL menuduh saya “lompat teori”—meminjam Durkheim, Turner, Bourdieu, Ricoeur—tanpa memahami konteksnya. Tuduhan ini tidak berdasar. Pendekatan interdisipliner dalam studi budaya justru wajar, sebab simbol sosial seperti Titi Jagung bersinggungan dengan ritual (Durkheim, Turner), relasi kuasa (Bourdieu), dan tindakan performatif (Austin).
Jika GDL ingin menunjukkan bahwa saya salah, ia perlu menandai di mana letak kesalahan penerapan teori itu. Namun sejauh ini, tuduhannya bersifat retoris tanpa pembuktian. Ia menyerang gaya, bukan isi. Kritik yang menyerang gaya tanpa memeriksa substansi teoritik hanyalah teater intelektual, bukan dialektika ilmiah.
Soal Posisi “Menang–Kalah” dalam Arena Wacana
GDL mengoreksi pertanyaan saya “siapa yang menang?” dengan menegaskan bahwa bupati memiliki posisi hegemonik—akses media, humas, dan sumber daya politik. Saya setuju, posisi struktural memang tidak simetris. Namun, saya tidak pernah menulis bahwa warga dan pejabat setara. Saya berbicara tentang negosiasi makna, bukan ilusi kesetaraan.
GDL membangun straw man argument dengan memelintir gagasan saya. Saya justru menegaskan bahwa simbol adalah medan tafsir yang terbuka, tempat warga, ASN, dan pemimpin saling menafsir ulang tanda sosial. Kuasa hadir, tetapi tidak absolut.
“Ventriloquism”, Subaltern, dan Kerendahan Hati Teoritis
GDL menolak penggunaan Spivak dan konsep subaltern dengan alasan konteks kolonialisme global tidak relevan di Lembata. Ia menuduh saya menjadi ventriloquist—berbicara atas nama rakyat tanpa menghadirkan suara asli mereka.
Padahal dalam tulisan “Ketika Kecurigaan Menjadi Dogma,” saya secara eksplisit menolak ventriloquism. Saya menulis: “Hermeneutika lupa pulang adalah hermeneutika yang berhenti di menara gading teori.”
Saya justru mengundang agar kita mendengar suara ibu-ibu jagung titi secara langsung. Ironisnya, GDL sendiri berbicara atas nama mereka tanpa menghadirkan testimoni empiris, wawancara, atau data ekonomi. Dalam konteks ini, GDL bukan lagi pembebas suara, melainkan penjaga gerbang wacana yang baru.
Ambivalensi dan Rekonsiliasi: Ilusi atau Ruang Harapan?
GDL menilai bahwa gagasan rekonsiliasi simbolik yang saya usulkan hanyalah ilusi tanpa pengakuan struktural dari pemerintah. Ia menegaskan, “negosiasi hanya mungkin bila peserta setara.”
Saya menghargai kritik itu—rekonsiliasi memang harus diiringi kebijakan nyata: proteksi pasar, rantai pasok, dan dukungan bagi petani. Namun menolak simbol sepenuhnya sama saja menolak ruang harapan. Simbol bukan penutup luka, tetapi bahasa untuk memulai penyembuhan sosial.
Ritual seperti Titi Jagung bisa saja dimanfaatkan pejabat, tetapi juga bisa menjadi ritual perjumpaan. Ia bukan solusi akhir, tetapi langkah awal menuju perubahan.
Rekonsiliasi simbolik yang disertai tindakan struktural justru membuka ruang kebijakan partisipatif. Menolak simbol berarti menolak peluang dialog.
Tentang “Office Space” dan Tantangan Empiris
GDL mengklaim dirinya telah menawarkan jalan “restoratif” dalam artikelnya Office Space, Logika Minimalis Pemda dan Rapuhnya Birokrasi Kita. Namun, argumen tentang birokrasi kering tidak otomatis membuktikan tesis tentang Titi Jagung.
Menyebut karya sendiri di bidang lain bukan bukti empiris bagi pernyataan baru. Jika GDL ingin membuktikan bahwa festivalisasi budaya di Lembata hanyalah “mobilisasi simbolik kosong,” ia perlu menghadirkan data: berapa produksi jagung titi sebelum dan sesudah lomba, apakah ada kenaikan pendapatan ibu-ibu pelaku, bagaimana rantai pasok dan kebijakan Pemda setelah festival. Tanpa itu, kritiknya tetap retorik—berisik secara ideologis, tapi sepi secara empiris.
Tentang Konsistensi yang Retak
Jika kita membaca kembali seluruh siklus tulisan GDL — dari “Wajah Simbolik Jabatan,” lalu “Teks, Konteks, dan Risiko Hipokrisi,” hingga yang terakhir “Kemunduran Ideologis” — kita menemukan pola yang sama: Ia selalu membuka dengan niat baik “membela subaltern,” tetapi selalu berakhir dengan meneguhkan dirinya sebagai satu-satunya pembaca sah realitas. Ia menolak teori yang berbeda, mengabaikan tanggapan yang sudah menjawab pertanyaannya, lalu menulis ulang seolah belum pernah ada diskusi sebelumnya.
Dengan kata lain, GDL tidak sedang berdialog; ia sedang mengulang monolog. Dan monolog yang terus diulang dengan gaya akademik hanyalah bentuk lain dari dogma.
Menutup Perdebatan yang Telah Kehilangan Arah
Semua tuduhan GDL sudah dijawab—baik di level konseptual, teoritis, maupun etis. Jika GDL tetap menulis balasan baru, itu akan berada pada level retoris, bukan substantif. Maka, saya memilih berhenti di sini—bukan karena tak mampu menjawab, tetapi karena debat ini telah kehilangan nilai dialogiknya.
Hermeneutik mengajarkan kita untuk memahami, bukan menaklukkan. Dan ketika lawan bicara berhenti memahami, percakapan berubah menjadi gema tanpa arah. Saya menutup perdebatan ini bukan karena menyerah, melainkan karena sadar bahwa perdebatan tanpa titik temu mudah berubah menjadi monopoli kata—alih-alih melahirkan pembaruan kebijakan nyata.
Sejak awal, kita memang berbeda jalan: GDL memilih kecurigaan absolut, saya memilih hermeneutika yang terbuka. Jika GDL ingin terus berdebat tentang “kedalaman”, saya persilakan. Tetapi saya berhenti di sini, bukan karena kalah, melainkan karena tak ingin perdebatan ini menjelma menjadi ritual kritik semata—tanpa ruang bagi tindakan dan kehadiran manusia.
Jika GDL menuduh saya “mengajak tenggelam di kolam dangkal,” biarlah ia terus menaburkan kata itu. Saya tetap memilih berenang—di mana pun airnya, dangkal atau dalam—asal masih bisa mendengar suara manusia di dalamnya. Di dasar kolam yang dangkal pun, wajah kemanusiaan masih bisa terlihat jelas. Sementara di menara teori yang terlalu tinggi, barangkali yang tersisa hanyalah gema suara sendiri.
Saya menulis ini bukan untuk menambah panjang daftar sanggahan, tetapi untuk menutup lingkaran yang sudah berputar terlalu lama. Sebab perdebatan tanpa titik temu hanya akan menumbuhkan kebisingan, bukan pengetahuan.
Saya menghormati GDL sebagai intelektual NTT yang tajam dan penuh gairah. Namun, saya menolak cara berpikir yang menjadikan kritik sebagai agama baru—di mana setiap tafsir lain dianggap dosa. Hermeneutika yang baik tidak berhenti pada kecurigaan, melainkan berani menaruh diri dalam kerendahan hati untuk mungkin keliru.
Maka, biarlah perdebatan ini berakhir di sini—bukan dengan kemenangan siapa pun, melainkan dengan kesadaran bahwa memahami selalu lebih luhur daripada menundukkan.
Epilog: Jalan Pulang Hermeneutika
Saya percaya, saya dan GDL, hanya sedang berjalan di jalan hermeneutika yang sama—jalan mencari makna di tengah kebisingan tanda. Bedanya, saya memilih untuk pulang: kembali ke manusia, ke konteks, ke ruang di mana teori tidak hanya berbicara, tetapi juga mendengar.
Karena filsafat yang tak mampu mendengarkan manusia pada akhirnya hanyalah ide tanpa jiwa.
Dan di situlah saya memilih berhenti. Bukan karena kalah, tetapi karena sadar: perdebatan ini telah berubah dari pencarian makna menjadi perebutan podium. Saya tidak menginginkan podium. Saya hanya menginginkan ruang dengar.
“Kecurigaan yang tak mau disembuhkan hanyalah luka yang dirawat. Sedangkan hermeneutika yang tulus adalah keberanian untuk mengakui: mungkin lawan bicara kita, bukan kita sendiri, yang sedang benar.” Kupang Kota Kasih, Oktober 2025