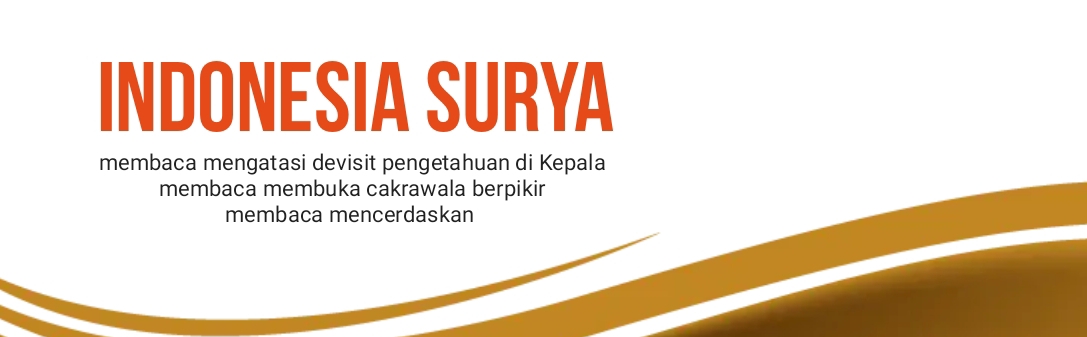Seandainya politik benar-benar dimaknai sebagai anugerah, tentu rakyat tidak harus menelan pil pahit sebagaimana yang dirasakan hari ini.
Politik sejatinya hadir sebagai ruang pengabdian dan pelayanan terhadap kepentingan publik. Namun dalam kenyataannya, politik justru sering tampil dalam bentuk yang telah “dibungkus rapi” oleh nafsu berkuasa.
Kekuasaan —diperjualbelikan lewat janji manis di panggung kampanye, terpampang di baliho, dan berseliweran di media sosial maupun media massa.
Dalam lintasan sejarah bangsa, rakyat belum sepenuhnya menikmati kesejahteraan dan kemerdekaan yang sejati, sebab sebagian besar ruang kehidupannya telah dirampas oleh ambisi dan kerakusan para pemegang kekuasaan.
Politik, dalam pandangan klasik, sering disebut sebagai ibu dari kekuasaan. Namun ironisnya, ia juga melahirkan “keadilan” sebagai anak haram, sebab keadilan kerap lahir dari kompromi yang cacat, tawar-menawar yang kotor, serta kepentingan yang tersembunyi.
Dalam konteks ini, pandangan Machiavelli menjadi relevan. Ia menilai bahwa kekuasaan memiliki otonomi yang terpisah dari nilai moral dan agama.
Bagi Machiavelli, seorang penguasa diperbolehkan berbohong, menipu, bahkan menindas, asalkan hal itu dilakukan demi kepentingan negara dan kelangsungan kekuasaan.
Pandangan ini seolah menemukan cerminnya dalam praktik politik Indonesia hari ini—penuh intrik, kepalsuan, dan kompromi moral yang membuat keadilan seringkali terpinggirkan. Kekuasaan akhirnya berubah menjadi supremasi, bukan lagi alat untuk melayani rakyat.
Tidak heran jika di mata rakyat, politik tampak pahit dan kotor.
Analogi yang paling dekat mungkin seperti secangkir kopi : bagi sebagian orang, kopi adalah kenikmatan; bagi yang lain, ia bisa menjadi penyebab penyakit lambung. Ada yang memandang kopi sebagai simbol energi untuk meraih cita-cita, namun juga ada yang menikmatinya sebagai pelarian dari kenyataan yang pahit.
Begitulah politik — ia bisa menjadi sarana menuju kemajuan dan kesejahteraan, tetapi juga bisa berubah menjadi sumber penderitaan, korupsi, dan ketidakadilan yang menggerogoti harapan rakyat kecil.
Lebih jauh, politik Indonesia hari ini beroperasi dalam lingkaran kekuasaan yang didominasi oleh relasi keluarga, kepentingan partai, dan kelompok ekonomi tertentu. Keputusan politik seringkali tidak lagi ditentukan oleh sistem yang sehat, melainkan oleh jaringan oligarki yang berusaha mempertahankan status quo.
Jeffrey A. Winters menggambarkan oligarki sebagai politik pertahanan kekayaan oleh segelintir elite yang menggunakan kekuasaan untuk melindungi kepentingan material mereka. Sementara itu, Wijayanto dari Universitas Diponegoro menilai bahwa sepanjang era reformasi, oligarki politik justru menguat, terutama pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Oligarki menggunakan partai politik sebagai kendaraan untuk menempatkan kader-kadernya di berbagai posisi strategis, memastikan bahwa kebijakan publik tidak mengancam kepentingan mereka. Fenomena ini memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia berjalan di atas rel oligarkis yang mengekang aspirasi rakyat.
Akhirnya, rakyat kecil tetap menjadi pihak yang menanggung konsekuensi dari permainan kekuasaan. Mereka menelan “pil pahit politik” yang terus diproduksi oleh nafsu berkuasa para elit.
Jika demikian, muncul pertanyaan yang menggugah nurani: sampai kapan kita harus percaya pada politik dan kekuasaan yang terus-menerus menyuguhkan rasa pahit yang sama?
Mungkin sudah saatnya politik kembali dimaknai sebagai ruang pengabdian, bukan sekadar medan perebutan kekuasaan. Sebab hanya dengan begitu, rakyat dapat benar-benar merasakan politik sebagai anugerah, bukan kutukan. (Miki Da,Lopez)